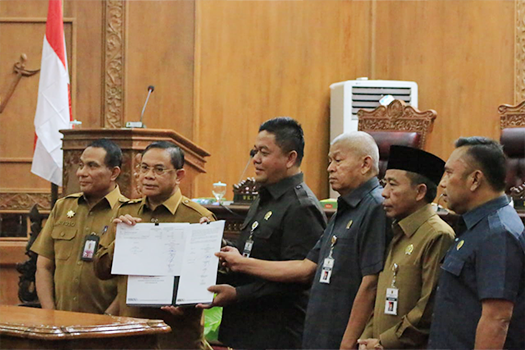MARKUS DAN MAFIA PERADILAN
Pada umumnya “markus” juga bisa dilakukan oleh Penegak Hukum itu
sendiri, baik secara langsung atau tidak langsung dengan cara
menggunakan orang lain sebagai perantara yang diciptakannya sendiri.
Sedang Mafia Peradilan di sini lebih dimaksudkan pada hukum dalam
praktik, dimana system dan budaya penegakan hukum yang dijalankan oleh
para Penegak Hukum, memberikan peluang untuk diselewengkan, dimana
secara implisit “hukum dan keadilan” telah berubah menjadi suatu
komoditas yang dapat diperdagangkan, tergantung siapa yang memesannya.
Hukum dan keadilan dapat dibeli oleh mereka orang-orang berduit,
sehingga ia menjadi barang mahal di negeri ini.
Adapun antara Makelar kasus (markus) dengan Mafia Peradilan adalah dua hal yang saling bersinergi atau saling membutuhkan, bahkan dalam praktiknya kadang tidak bisa dipisahkan. Mafia Peradilan spektrumnya jauh lebih luas dari Makelar Kasus. Di negeri ini Law Enforcement diibaratkan bagai menegakkan benang basah kata lain, dari kata “sulit dan susah untuk diharapkan”. Salah satu indikator yang mempersulit penegakan hukum di Indonesia adalah maraknya “budaya korupsi” yang terjadi hampir disemua birokrasi dan stratifikasi sosial, sehingga telah menjadikan upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, baik markus maupun mafia peradilan hanya sebatas retorika yang berisikan sloganitas dari pidato-pidato kosong belaka. Bahkan secara faktual tidak dapat dipungkiri semakin banyak undang-undang yang lahir maka hal itu berbanding lurus semakin banyak pula komoditas yang dapat diperdagangkan. Ironisnya tidak sedikit pula bagian dari masyarakat kita sendiri yang terpaksa harus membelinya. Di sini semakin tanpak bahwa keadilan dan kepastian hukum tidak bisa diberikan begitu saja secara gratis kepada seseorang jika disaat yang sama ada pihak lain yang menawarnya. Kenyataan ini memperjelas kepada kita hukum di negeri ini “tidak akan pernah” memihak kepada mereka yang lemah dan miskin. “ Sekali lagi tidak akan pernah… ! ”
Sindiran yang sifatnya sarkatisme mengatakan, “berikan aku hakim yang baik, jaksa yang baik, polisi yang baik dengan undang-undang yang kurang baik sekalipun, hasil yang akan aku capai pasti akan lebih baik dari hukum yang terbaik yang pernah ada dinegeri ini”. Tapi agaknya para Penegak Hukum, Politisi, Pejabat dan Tokoh-Tokoh tertentu dalam masyarakat kita tidak akan punya waktu dan ruang hati untuk dapat mengubris segala bentuk sindiran yang mempersoalkan eksistensi pekerjaan dan tanggungjawab mereka kepada publik. Lebih baik tebal muka dan tidak punya rasa malu, dari pada menggubris sindiran publik yang bakal mengurangi rejeki mereka.
Buruknya kinerja para Penegak Hukum dan buruknya system pengawasan yang ada dalam proses penegakan hukum, telah melahirkan stigmatisasi mafia hukum dan mafia peradilan termasuk makelar kasus (markus) di Indonesia. Kenyataan ini bila kita telusuri keberadaannya ternyata mengakar pada kebudayaan mentalitas kita sebagai suatu bangsa. Sehingga apa yang disebut dengan “markus” dan “mafia peradilan” eksistensinya cenderung abadi karena ia telah menjadi virus mentalitas yang membudaya dalam proses penegakan hukum di negeri ini.
Oleh karenanya berbicara tentang Law Enforcement di Indonesia tidaklah bisa dengan hanya memecat para Hakim, memecat para Jaksa dan memecat para Polisi yang korup, akan tetapi perbaikan tersebut haruslah dimulai dengan pembangunan pendidikan dengan pendekatan pembangunan kebudayaan mentalitas kita sebagai suatu bangsa dan menjadikan moral force yang berlandaskan pada Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai basic guna terbangunnya budaya sikap dan prilaku para Penegak hukum di Indonesia. Tanpa itu, semuanya menjadi utopia belaka ! ( Desember 2009 )
Adapun antara Makelar kasus (markus) dengan Mafia Peradilan adalah dua hal yang saling bersinergi atau saling membutuhkan, bahkan dalam praktiknya kadang tidak bisa dipisahkan. Mafia Peradilan spektrumnya jauh lebih luas dari Makelar Kasus. Di negeri ini Law Enforcement diibaratkan bagai menegakkan benang basah kata lain, dari kata “sulit dan susah untuk diharapkan”. Salah satu indikator yang mempersulit penegakan hukum di Indonesia adalah maraknya “budaya korupsi” yang terjadi hampir disemua birokrasi dan stratifikasi sosial, sehingga telah menjadikan upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, baik markus maupun mafia peradilan hanya sebatas retorika yang berisikan sloganitas dari pidato-pidato kosong belaka. Bahkan secara faktual tidak dapat dipungkiri semakin banyak undang-undang yang lahir maka hal itu berbanding lurus semakin banyak pula komoditas yang dapat diperdagangkan. Ironisnya tidak sedikit pula bagian dari masyarakat kita sendiri yang terpaksa harus membelinya. Di sini semakin tanpak bahwa keadilan dan kepastian hukum tidak bisa diberikan begitu saja secara gratis kepada seseorang jika disaat yang sama ada pihak lain yang menawarnya. Kenyataan ini memperjelas kepada kita hukum di negeri ini “tidak akan pernah” memihak kepada mereka yang lemah dan miskin. “ Sekali lagi tidak akan pernah… ! ”
Sindiran yang sifatnya sarkatisme mengatakan, “berikan aku hakim yang baik, jaksa yang baik, polisi yang baik dengan undang-undang yang kurang baik sekalipun, hasil yang akan aku capai pasti akan lebih baik dari hukum yang terbaik yang pernah ada dinegeri ini”. Tapi agaknya para Penegak Hukum, Politisi, Pejabat dan Tokoh-Tokoh tertentu dalam masyarakat kita tidak akan punya waktu dan ruang hati untuk dapat mengubris segala bentuk sindiran yang mempersoalkan eksistensi pekerjaan dan tanggungjawab mereka kepada publik. Lebih baik tebal muka dan tidak punya rasa malu, dari pada menggubris sindiran publik yang bakal mengurangi rejeki mereka.
Buruknya kinerja para Penegak Hukum dan buruknya system pengawasan yang ada dalam proses penegakan hukum, telah melahirkan stigmatisasi mafia hukum dan mafia peradilan termasuk makelar kasus (markus) di Indonesia. Kenyataan ini bila kita telusuri keberadaannya ternyata mengakar pada kebudayaan mentalitas kita sebagai suatu bangsa. Sehingga apa yang disebut dengan “markus” dan “mafia peradilan” eksistensinya cenderung abadi karena ia telah menjadi virus mentalitas yang membudaya dalam proses penegakan hukum di negeri ini.
Oleh karenanya berbicara tentang Law Enforcement di Indonesia tidaklah bisa dengan hanya memecat para Hakim, memecat para Jaksa dan memecat para Polisi yang korup, akan tetapi perbaikan tersebut haruslah dimulai dengan pembangunan pendidikan dengan pendekatan pembangunan kebudayaan mentalitas kita sebagai suatu bangsa dan menjadikan moral force yang berlandaskan pada Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai basic guna terbangunnya budaya sikap dan prilaku para Penegak hukum di Indonesia. Tanpa itu, semuanya menjadi utopia belaka ! ( Desember 2009 )
Komentar (0)
Tuliskan Komentar Anda