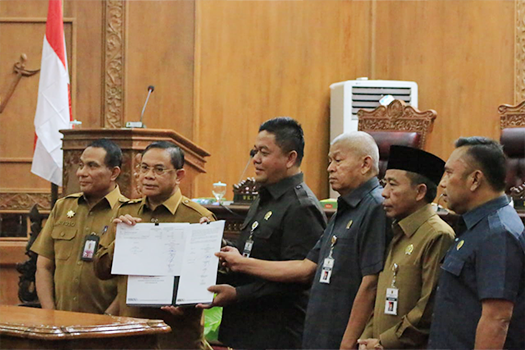Memahami Kemunculan Teroris Internasional
Fenomena munculnya postur dan style teroris internasional yang
demikian, bukanlah tanpa alasan dan lahir secara mendadak. Mengikuti
Teori Sistem Dunia Modern (TSDM)-nya Immanuel Wallerstein, kemunculan
teroris internasional merupakan bagian dari dialektika sejarah
pertarungan politik internasional yang bermula sejak 500 tahun yang
lalu. Dimana pada awal abad duapuluh satu ini, merupakan momentum
puncak dari dari pertarungan tersebut.
Tesis utama Wallerstein dalam kaitan ini adalah bahwa sistem dunia kapitalis-liberalis yang kini berkuasa merupakan faktor utama yang menyebabkan kehancuran negara-negara dunia ketiga. Perang Dunia (PD) I yang terjadi di awal abad 20, meski yang jadi aktor antagonisnya adalah Jerman (ditambah Jepang dan Itali), yang hancur justru imperium Turki Utsmani. Begitu pula halnya dengan PD II, meski Jepang yang dibom atom pada tahun 1945, yang rusak sistem kehidupannya adalah negara-negara jajahan yang umumnya kini dikenal dengan istilah negara-negara dunia ketiga.
Karena itu, akan menjadi ahistoris bila memahami teroris internaional tidak dimulai dari sini. Paling tidak, ada tiga tahapan yang saling berkaitan dari kemunculan teroris internasional saat ini. Pertama, tahap terjadinya ketidakseimbangan global, atau meminjam istilah Huntington, fenomena ini dikenal dengan the global paradox.
Tahapan ini semakin menemukan bentuknya yang ideal, manakala Uni Soviet runtuh. Otomatis, struktur politik berubah dari bipolaris ke unipolaris. Kemunculan kekuatan unipolaris dari kelompok negara-negara maju, dalam pandangan mazhab realis, semakin memperkuat bairgaining position kelompok negara-negara pengendali di satu pihak, dan memperlemah power position negara-negara yang kontra-pengendali. Dengan peta politik seperti ini, sumber-sumberdaya internasional akan cenderung dikuasai oleh kelompok pengendali tersebut.
Hubungan internasional yang seperti tergambar di atas, bukanlah suatu hubungan yang dikehendaki oleh aktor-aktor internasional. Bila mengikuti pemikiran Thomas Hobbes, dimana setiap orang secara alamiah akan mengejar kesenangan dan menghindari kesengsaraan, setiap negara akan mengejar kesenangan (inti dari national interest-nya). Karena itu, setiap negara akan terlibat dalam proses perburuan (rent seeking) tiada henti terhadap sumber-sumberdaya internasional yang tersedia. Bila percaturan politik internasional yang terjadi sekarang seperti yang tergambar di atas, maka negara-negara yang terhegemoni atau terkooptasi oleh kelompok negara-negara pengendali, secara alamiah akan melakukan perlawanan.
Kondisi “pertarungan” yang tidak seimbang tersebut, telah melahirkan tahapan kedua, yakni regionalisasi yang terbentuk mengiringi tatanan dunia yang unipolaris. Regionalisasi politik tersebut menjadi bagian dari perlawanan terhadap kelompok negara-negara pengendali. Dalam bentuknya yang formal, regionalisasi dapat dilihat pada Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 yang kemudian melahirkan Gerakan Non Blok (GNB). Begitu juga dengan pembentukan Association of South East Asian Nations (ASEAN), Liga Arab, dan Uni Afrika. Dalam bentuknya yang terkini, regionalisasi dapat dilihat pada pembentukan Uni Eropa, Blok Cina-India, ASEAN Plus 3, dan lain sebagainya. Hampir tidak ada kawasan di dunia ini, yang tidak memiliki organisasi regional.
Regionalisasi politik yang terjadi di era unipolaris sekarang ini, dalam bentuk kapabilitasnya yang sekecil apapun, ia akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempengaruhi keseimbangan global. Karena dalam proses regionalisasi akan banyak terjadi transaksi politik. Dari transaksi ini, akan banyak muncul varian-varian hubungan yang terbentuk, baik di dalam kelompok negara-negara kontra-pengendali, maupun varian hubungan diagonalis di antara kelompok negara-negara kontra-pengendali dengan kelompok negara-negara pengendali, atau dengan kelompok negara-negara pendukungnya. Hasil dari berbagai varian dalam hubungan internasional tersebut, adalah hubungan politik yang semakin kusut (confuse). Hal ini disebabkan karena kerapkali terjadi pembiasan penafsiran dari kepentingan nasional (natonal interest) masing-masing negara.
Aliansi regional yang diharapkan mampu membuat tatanan dunia yang multipolaris, ternyata gagal. Sekedar contoh, invasi Amerika Serikat sebagai negara pengendali utama dan sekutu-sekutunya ke Afganistan dan Irak, tidak dapat dibendung oleh organisasi-organisasi regional tersebut. Bahkan, oleh badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sekalipun. Hal ini menunjukkan sebuah kegagalan dari perlawanan “terselubung” melalui organisasi formal dari negara-negara yang terhegemoni. Kegagalan ini juga berarti bahwa pendekatan normatif, yang diusung oleh para penganut paham idealis, tidak efektif. Karena itu, kegagalan ini memberikan pesan bahwa perlawanan terhadap kelompok negara-negara pengendali, mesti dilakukan dengan merubah strategi perlawanan.
Pada 192 negara yang tersebar di dunia ini, posisi elit-elit berkuasa yang menentukan arah kebijakan luar negeri sebuah negara, bisa saja berubah. Tapi, ideologi yang dianut oleh warga negaranya tidak akan berubah. Kalau saja terjadi transmigrasi ideologi, jumlahnya tidaklah signifikan. Karenanya, meski pun sebuah pemerintahan tidak merubah strategi perlawanannya terhadap hegemoni kelompok negara-negara pengendali ---karena berbagai pertimbangan (national power-nya)--, warga negara atau kelompok ideologis yang berada dalam sebuah pemerintahan tersebut, bisa merubah strategi perlawanannya. Logika dari kalimat ini juga berarti bahwa sangat mungkin sebuah negara merubah strategi perlawanannya, dengan varian yang berbeda-beda pada tiap negara. Kasus Afganistas di era Taliban dan Irak di era Saddam, membuktikan hal ini.
Negara-negara yang terhegemoni, umumnya tidak punya banyak pilihan dalam menentukan pilihan strategi perlawanannya pada saat negara itu mengambil sikap untuk merubah strateginya. Karenanya, kemunculan berbagai International Non Government Organizations (INGOs) sebagai Non State Actors pada percaturan politik internasional, bisa dianggap menjadi bagian dari pilihan strategi yang diambil. Penggunaan INGOs sebagai instrumen strategik, merupakan pilihan strategi politik yang aman. Karena pada satu sisi, tekanan-tekanan politiknya bisa mempengaruhi kebijakan politik global, tetapi pada sisi lain, INGOs bukanlah subjek hukum internasional yang dapat dikenai sanksi internasional, sebagaimana halnya sebuah negara. Karena itu, pasca runtuhnya struktur internasional dari bipolar ke unipolar, perkembangan INGOs sangatlah pesat. Perkembangan yang pesat itu, tentu tidak akan terjadi bila tidak ada dukungan politik dan finansial dari pemerintah. Dalam bentuknya yang riil, di beberapa negara ditemukan istilah “LSM Plat Merah”, untuk merujuk pada NGOs atau INGOs yang bekerja untuk kepentingan pemerintah.
Dalam beberapa kasus lain, keberadaan NGOs atau INGOs ini berhasil memperjuangkan kepentingan nasional dari negara-negara berkembang dan miskin yang terkooptasi. Misalnya, tuntutan penghapusan hutang, tekanan terhadap IMF, WTO, World Bank, dan institusi-institusi “Brettonwoods” lainnya. Sebaliknya, kelompok negara-negara pengendali hanya bisa menekan INGOs tersebut melalui pemerintah dimana INGOs itu berada.
Posisi NGOs atau INGOs dalam sebuah negara bagaikan sebuah bola bilyar. Mereka akan menembak kemana saja tergantung ke arah mana mereka ditembakkan. Dan arah mana yang dituju, tentu sangat tergantung pada siapa yang menembakkan. Logika ini dapat dipahami karena NGOs dan INGOs sangat tergantung pada dana yang tersedia. Oleh karena itu, para sponsor dari NGOs atau INGOs sangat memegang peranan penting dalam menentukan ke arah mana NGOs atau INGOs itu bergerak.
Menyadari bahwa NGOs atau INGOs bisa dijadikan instrumen strategik oleh kelompok negara-negara terhegemoni, maka kelompok negara-negara pengendali juga pada akhirnya menggunakan INGOs ini sebagai instrumen yang mampu mengcounter-nya. Dalam kebijakannya yang ekstrem, kelompok negara-negara pengendali ini seringkali menggunakan INGOs sebagai agen-agen spionase atau agen-agen penyebar ideologi liberalis-kapitalis, yang selama ini dianut oleh kelompok negara-negara pengendali. Dalam bentuknya yang minimal, kelompok negara-negara pengendali ini, berusaha menyetir (membelokkan) arah gerakan INGOs melalui pemberian bantuan-bantuan keuangan.
Kenyataan di atas, merupakan gambaran pahit bagi kelompok negara-negara kontra-pengendali. Dan tahapan ketiga lahir, berangkat dari kesadaran kelompok kontra-pengendali akan resources-nya yang terbatas. Karenanya, dalam perspektif ketiga inilah, kemunculan terorisme bisa dipahami. Dalam logika tahapan ini, terorisme adalah strategi yang paling aman bagi sebuah negara (atau kelompok-kelompok tertentu) untuk melakukan perlawanan terhadap kelompok negara-negara pengendali, namun lepas dari sanksi internasional yang melekat pada statusnya sebagai state actor dalam percaturan internasional.
Tesis utama Wallerstein dalam kaitan ini adalah bahwa sistem dunia kapitalis-liberalis yang kini berkuasa merupakan faktor utama yang menyebabkan kehancuran negara-negara dunia ketiga. Perang Dunia (PD) I yang terjadi di awal abad 20, meski yang jadi aktor antagonisnya adalah Jerman (ditambah Jepang dan Itali), yang hancur justru imperium Turki Utsmani. Begitu pula halnya dengan PD II, meski Jepang yang dibom atom pada tahun 1945, yang rusak sistem kehidupannya adalah negara-negara jajahan yang umumnya kini dikenal dengan istilah negara-negara dunia ketiga.
Karena itu, akan menjadi ahistoris bila memahami teroris internaional tidak dimulai dari sini. Paling tidak, ada tiga tahapan yang saling berkaitan dari kemunculan teroris internasional saat ini. Pertama, tahap terjadinya ketidakseimbangan global, atau meminjam istilah Huntington, fenomena ini dikenal dengan the global paradox.
Tahapan ini semakin menemukan bentuknya yang ideal, manakala Uni Soviet runtuh. Otomatis, struktur politik berubah dari bipolaris ke unipolaris. Kemunculan kekuatan unipolaris dari kelompok negara-negara maju, dalam pandangan mazhab realis, semakin memperkuat bairgaining position kelompok negara-negara pengendali di satu pihak, dan memperlemah power position negara-negara yang kontra-pengendali. Dengan peta politik seperti ini, sumber-sumberdaya internasional akan cenderung dikuasai oleh kelompok pengendali tersebut.
Hubungan internasional yang seperti tergambar di atas, bukanlah suatu hubungan yang dikehendaki oleh aktor-aktor internasional. Bila mengikuti pemikiran Thomas Hobbes, dimana setiap orang secara alamiah akan mengejar kesenangan dan menghindari kesengsaraan, setiap negara akan mengejar kesenangan (inti dari national interest-nya). Karena itu, setiap negara akan terlibat dalam proses perburuan (rent seeking) tiada henti terhadap sumber-sumberdaya internasional yang tersedia. Bila percaturan politik internasional yang terjadi sekarang seperti yang tergambar di atas, maka negara-negara yang terhegemoni atau terkooptasi oleh kelompok negara-negara pengendali, secara alamiah akan melakukan perlawanan.
Kondisi “pertarungan” yang tidak seimbang tersebut, telah melahirkan tahapan kedua, yakni regionalisasi yang terbentuk mengiringi tatanan dunia yang unipolaris. Regionalisasi politik tersebut menjadi bagian dari perlawanan terhadap kelompok negara-negara pengendali. Dalam bentuknya yang formal, regionalisasi dapat dilihat pada Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 yang kemudian melahirkan Gerakan Non Blok (GNB). Begitu juga dengan pembentukan Association of South East Asian Nations (ASEAN), Liga Arab, dan Uni Afrika. Dalam bentuknya yang terkini, regionalisasi dapat dilihat pada pembentukan Uni Eropa, Blok Cina-India, ASEAN Plus 3, dan lain sebagainya. Hampir tidak ada kawasan di dunia ini, yang tidak memiliki organisasi regional.
Regionalisasi politik yang terjadi di era unipolaris sekarang ini, dalam bentuk kapabilitasnya yang sekecil apapun, ia akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempengaruhi keseimbangan global. Karena dalam proses regionalisasi akan banyak terjadi transaksi politik. Dari transaksi ini, akan banyak muncul varian-varian hubungan yang terbentuk, baik di dalam kelompok negara-negara kontra-pengendali, maupun varian hubungan diagonalis di antara kelompok negara-negara kontra-pengendali dengan kelompok negara-negara pengendali, atau dengan kelompok negara-negara pendukungnya. Hasil dari berbagai varian dalam hubungan internasional tersebut, adalah hubungan politik yang semakin kusut (confuse). Hal ini disebabkan karena kerapkali terjadi pembiasan penafsiran dari kepentingan nasional (natonal interest) masing-masing negara.
Aliansi regional yang diharapkan mampu membuat tatanan dunia yang multipolaris, ternyata gagal. Sekedar contoh, invasi Amerika Serikat sebagai negara pengendali utama dan sekutu-sekutunya ke Afganistan dan Irak, tidak dapat dibendung oleh organisasi-organisasi regional tersebut. Bahkan, oleh badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sekalipun. Hal ini menunjukkan sebuah kegagalan dari perlawanan “terselubung” melalui organisasi formal dari negara-negara yang terhegemoni. Kegagalan ini juga berarti bahwa pendekatan normatif, yang diusung oleh para penganut paham idealis, tidak efektif. Karena itu, kegagalan ini memberikan pesan bahwa perlawanan terhadap kelompok negara-negara pengendali, mesti dilakukan dengan merubah strategi perlawanan.
Pada 192 negara yang tersebar di dunia ini, posisi elit-elit berkuasa yang menentukan arah kebijakan luar negeri sebuah negara, bisa saja berubah. Tapi, ideologi yang dianut oleh warga negaranya tidak akan berubah. Kalau saja terjadi transmigrasi ideologi, jumlahnya tidaklah signifikan. Karenanya, meski pun sebuah pemerintahan tidak merubah strategi perlawanannya terhadap hegemoni kelompok negara-negara pengendali ---karena berbagai pertimbangan (national power-nya)--, warga negara atau kelompok ideologis yang berada dalam sebuah pemerintahan tersebut, bisa merubah strategi perlawanannya. Logika dari kalimat ini juga berarti bahwa sangat mungkin sebuah negara merubah strategi perlawanannya, dengan varian yang berbeda-beda pada tiap negara. Kasus Afganistas di era Taliban dan Irak di era Saddam, membuktikan hal ini.
Negara-negara yang terhegemoni, umumnya tidak punya banyak pilihan dalam menentukan pilihan strategi perlawanannya pada saat negara itu mengambil sikap untuk merubah strateginya. Karenanya, kemunculan berbagai International Non Government Organizations (INGOs) sebagai Non State Actors pada percaturan politik internasional, bisa dianggap menjadi bagian dari pilihan strategi yang diambil. Penggunaan INGOs sebagai instrumen strategik, merupakan pilihan strategi politik yang aman. Karena pada satu sisi, tekanan-tekanan politiknya bisa mempengaruhi kebijakan politik global, tetapi pada sisi lain, INGOs bukanlah subjek hukum internasional yang dapat dikenai sanksi internasional, sebagaimana halnya sebuah negara. Karena itu, pasca runtuhnya struktur internasional dari bipolar ke unipolar, perkembangan INGOs sangatlah pesat. Perkembangan yang pesat itu, tentu tidak akan terjadi bila tidak ada dukungan politik dan finansial dari pemerintah. Dalam bentuknya yang riil, di beberapa negara ditemukan istilah “LSM Plat Merah”, untuk merujuk pada NGOs atau INGOs yang bekerja untuk kepentingan pemerintah.
Dalam beberapa kasus lain, keberadaan NGOs atau INGOs ini berhasil memperjuangkan kepentingan nasional dari negara-negara berkembang dan miskin yang terkooptasi. Misalnya, tuntutan penghapusan hutang, tekanan terhadap IMF, WTO, World Bank, dan institusi-institusi “Brettonwoods” lainnya. Sebaliknya, kelompok negara-negara pengendali hanya bisa menekan INGOs tersebut melalui pemerintah dimana INGOs itu berada.
Posisi NGOs atau INGOs dalam sebuah negara bagaikan sebuah bola bilyar. Mereka akan menembak kemana saja tergantung ke arah mana mereka ditembakkan. Dan arah mana yang dituju, tentu sangat tergantung pada siapa yang menembakkan. Logika ini dapat dipahami karena NGOs dan INGOs sangat tergantung pada dana yang tersedia. Oleh karena itu, para sponsor dari NGOs atau INGOs sangat memegang peranan penting dalam menentukan ke arah mana NGOs atau INGOs itu bergerak.
Menyadari bahwa NGOs atau INGOs bisa dijadikan instrumen strategik oleh kelompok negara-negara terhegemoni, maka kelompok negara-negara pengendali juga pada akhirnya menggunakan INGOs ini sebagai instrumen yang mampu mengcounter-nya. Dalam kebijakannya yang ekstrem, kelompok negara-negara pengendali ini seringkali menggunakan INGOs sebagai agen-agen spionase atau agen-agen penyebar ideologi liberalis-kapitalis, yang selama ini dianut oleh kelompok negara-negara pengendali. Dalam bentuknya yang minimal, kelompok negara-negara pengendali ini, berusaha menyetir (membelokkan) arah gerakan INGOs melalui pemberian bantuan-bantuan keuangan.
Kenyataan di atas, merupakan gambaran pahit bagi kelompok negara-negara kontra-pengendali. Dan tahapan ketiga lahir, berangkat dari kesadaran kelompok kontra-pengendali akan resources-nya yang terbatas. Karenanya, dalam perspektif ketiga inilah, kemunculan terorisme bisa dipahami. Dalam logika tahapan ini, terorisme adalah strategi yang paling aman bagi sebuah negara (atau kelompok-kelompok tertentu) untuk melakukan perlawanan terhadap kelompok negara-negara pengendali, namun lepas dari sanksi internasional yang melekat pada statusnya sebagai state actor dalam percaturan internasional.
Komentar (0)
Tuliskan Komentar Anda