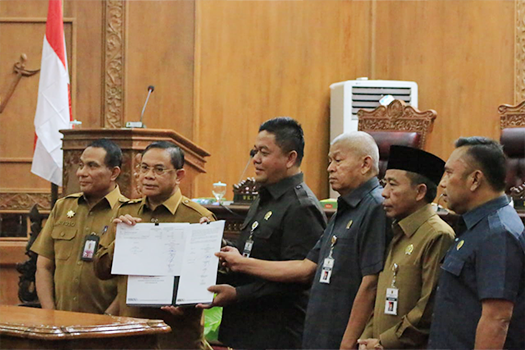Mitologisasi Ramadhan dan Kemerdekaan RI
Secara historis, mitologisasi kemerdekaan dalam hubungan antara Ramadhan dengan Agustus mulai dikemukakan tahun 1946, tepatnya pada saat Indonesia merayakan hari kemerdekaannya yang pertama. Pada saat itu, secara kebetulan atau tidak, berbagai pidato petinggi negara, mulai dari Presiden Soekarno, para gubernur, residen, bupati, wedana, camat, dan kepala desa, serta tidak terkecuali para pemimpin formal atau infomal mengaitkan spirit kemerdekaan rohani/jiwa yang diperoleh melalui puasa Ramadhan dengan kemerdekaan fisik 17 Agustus 1945 yang didapat dengan perjuangan lahir dan batin menentang para penjajah. Berbagai spanduk yang dipasang dan coretan yang dibuat saat itu juga berisikan pernyataan yang sama. Dari berbagai sumber sejarah diketahui, bahwa fenomena ini terjadi di hampir seluruh pelosok negeri, termasuk di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya non-muslim (yang tidak memahami Ramadhan sebagai bulan puasa).
Sejak tahun 1946 hingga saat
sekarang, dalam berbagai kesempatan, terutama bila Ramadhan datang
bersamaan dengan bulan Agustus, maka mitos-mitos tersebut kembali
diapungkan.
Tahun ini, aroma mitologisasi makna
kemerdekaan dari kesamaan masuknya Ramadhan dengan Agustus telah tercium
di atmosfer bangsa. Beberapa pejabat dan politisi khususnya serta
penceramah atau penulis umumnya telah menghangat-hangat hubungan antara
Ramadhan dengan kemerdekaan RI itu. Bahkan, ada yang mewacanakan bahwa
perayaan kemerdekaan RI yang jatuh pada bulan Ramadhan tahun ini
sejatinya diisi juga dengan ”pemerdekaan” atau pengampunan dan
pembebasan sebagian anak bangsa yang telah berbuat dosa (yang memaling
dan mengorup uang rakyat dan harta negara).
Mitologisasi akhir-akhir ini
(apalagi yang disebut terakhir di atas) sangat jauh bedanya dengan
mitos-mitos kesamaan antara Ramadhan dan kemerdekaan RI yang diciptakan
para pemimpin di masa lampau. Di masa lampau mitos itu diciptakan untuk
menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Mitos dibuat juga untuk
menghadirkan sikap mau berkorban dan rela menderita bagi anak negeri
guna kemerdekaan dan keutuhan bangsa. Penciptaan mitos tahun
1946—sebagai contoh—adalah sebagai bagian upaya pemimpin negeri untuk
menumbuhkan semangat perlawanan (patriotisme dan nasionalisme) anak
bangsa menghadapi kedatangan kembali Belanda (NICA) yang membonceng
bersama tentara sekutu. Di samping itu, mitos tahun 1946 tersebut dibuat
oleh para pemimpin yang telah teruji kenegarawannya. Mitos yang dibuat
dewasa ini (apalagi yang terakhir), cenderung tidak menyentuh
kepentingan keseluruhan anak bangsa dan tidak ditujukan untuk
kepentingan negara bangsa. Dan, sejalan dengan itu, para pencipta
mitosnya juga bukan para politisi dan pejabat yang mumpuni, mereka bukan
pemimpin dan bukan negarawan.
Mitos memang perlu, tetapi kalau
terlalu banyak mitos akan menimbulkan dampak negatif bagi pertumbuhan
jiwa anak bangsa. Apalagi sebagian mitos itu sesat, menyesatkan, serta
tidak cerdas. Padahal, pandangan, gagasan dan ide yang bernas, serta
orang cerdaslah yang dibutuhkan bangsa ini.
Karena itu, ketika kesadaran dan
kecerdasan serta kekritisan anak bangsa sudah demikian maju, selayaknya
mitologisasi itu ditinggalkan. Marilah kita kembali ”ke bumi”, kembali
kepada kenyataan sehari-hari warga bangsa dan negara ini. Warga bangsa
yang masih banyak menderita dan negara yang masih dibelit beragam
masalah. Para pejabat dan politisi khususnya dan penceramah atau
pengamat/peminat sosial keagamaan umumnya sudah sepantasnya meninggalkan
segala mitos sesat, menyesatkan dan tidak cerdas itu, serta
beralihkanlah guna menghadirkan pernyataan, pidato, ceramah dan tulisan
yang realistis dan mencerdaskan.
Bila tidak mitos-mitos yang
dihadirkan tersebut akan menjadi bumerang, sebab anak bangsa yang cerdas
dan kritis dengan segera mengetahui bahwa apa yang diucapkan,
dipidatokan, diceramahkan atau dituliskan hanyalah omong kosong semata,
lain yang diucapkan/dituliskan lain pula yang dilakukan. Karena itu,
marilah kita masuki dan jalani puasa Ramadhan, serta kita rayakan
kemerdekaan RI dengan menyelaraskan niat dengan amalan dan menyesuaikan
kata dengan perbuatan. (*)
[ Red/Redaksi_ILS ]