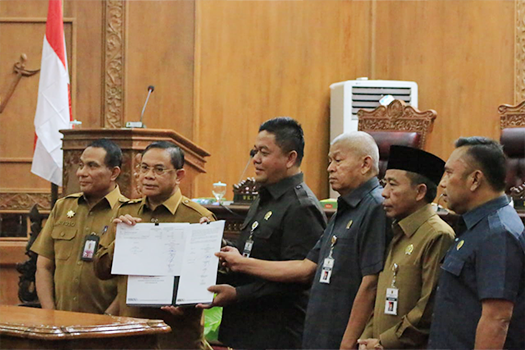Nahdlatul Ulama dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia
Kebangsaan dan Kemasyarakatan
Pada masa penjajahan, NU bersama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam lainnya -sepeti Serikat Dagang Islam dan Muhammadiyah- secara terbuka menentang kolonialisme.
NU antara lain mengeluarkan pernyataan yang menolak kerja rodi maupun milisi.
Cikal bakal NU -yang disusun oleh Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahab Hasbullah- memang berupa organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wathan, yang artinya Kebangkitan Tanah Air pada 1916.
Kemudian dua organisasi lain berdiri, yaitu Nahdlatul Tujjar dan sekolah Taswirul Afkar sebagai wahana pendidikan sosial politik dan keagamaan kaum santri.
"Ketiganya menjadi latar belakang sebelum NU berdiri. Nilai-nilai ketiga lembaga itu yang menjadi sebuah dasar untuk NU ke depan," kata Profesor Abdul A'la dari IAIN Sunan Ampel kepada BBC Indonesia.
Dengan nilai-nilai tersebut, maka politik kebangsaan dan kerakyatan di Nahdlatul Ulama tidak bisa ditawar-tawar lagi.
"NKRI setelah merdeka sudah tidak perlu dipersoalkan lagi. Kemudian politik kerakyatan, bagaimana memberdayakan masyarakat pedesaan menjadi masyarakat madani yang kokoh."
"Dua hal itu merupakan benang merah yang sama sekali tidak bisa diabaikan kalau berbicara tentang NU. Di atas kertas, itu merupakan komitmen," kata Profesor Abdul A'la.
Partai politik
Pada tahun 1952, Nahdlatul Ulama meninggalkan Masyumi dan setelah melalui perdebatan internal yang hangat, NU memproklamasikan diri sebagai partai politik pada tahun 1954.
"Tarik menarik kondisi sosial politik saat itu memang membuat NU terjebak dalam pusaran politik praktis dengan segala untung ruginya," kata Profesor Abdul A'la.
Setahun kemudian, dalam pemilu 1955, Partai Nahdlatul Ulama berhasil meraih suara terbesar ketiga dari 29 peserta pemilu: di bawah PNI dan Masyumi namun di atas PKI serta PSI.
Dalam pemilu 1971, NU bahkan berhasil berada di urutan ke dua, di bawah Golkar yang menikmati sejumlah fasilitas dan kemudahan dari pemerintah.
Namun menurut Profesor Abdul A'la, terjunnya NU ke partai politik kemudian menimbulkan sejumlah masalah.
"Realitas menunjukkan ketika terjun menjadi partai politik resmi, banyak lembaga-lembaga di NU, misanya tendang dakwah dan yang lainnya menjadi terbengkalai," tambahnya.
Oleh karena itu di kalangan NU, menurut Prof Abdul A'la, ada semacam komitmen bahwa terlibat dalam politik praktis kurang bermanfaat untuk pengembangan visi kebangsaan dan kerakyatan NU.
Kembali ke khittah
Gagasan NU untuk kembali ke khittah 1926 sebenarnya sudah mulai muncul pada Muktamar NU ke-26 di Semarang pada tahun 1979, setelah pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1975 menetapkan asas tunggal dalam partai politik dengan menyederhanakan peserta pemilu menjadi Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia.
NU sempat masuk ke dalam PPP, dengan 56 anggota NU dari total 99 anggota Fraksi Persatuan Pembangunan di DPR, dan sudah muncul keinginan untuk keluar dari partai politik berlambang khabah tersebut.
Dalam Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984 akhirnya diputuskan untuk kembali ke khittah 1926 dan keluar dari area politik praktis.
"Para elite NU dan mendapat dukungan dari masayarkat penuh, kemudian kembali ke khittah 1926, ke awal berdirinya NU," kenang Abdu' A'la.
Sejalan dengan reformasi politik pasca jatuhnya Presiden Suharto, muncul Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, yang merupakan saluran politik dari orang-orang dengan latar belakang NU.
"Menurut saya, seharusnya NU sebagai jamaah jangan terlalu masuk ke dalam politik praktis lagi," katanya.
"Okelah PKB didirikan oleh NU bagi orang yang mendirikan NU ke politik praktis. Tapi NU sebagai jamaah jangan mendukung total PKB karena itu hanya bagian kecil dari NU."
Profesor Abdul A'la mengatakan semestinya NU mendukung semua orang dengan berbagai latar belakang NU yang berada di partai manapun.
"Jangan PKB justru kemudian mengangkangi NU. Itu dulu yang sempat terjadi."
Tokoh sentral
Tahun 1984, NU memilih Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Kepemimpinan Gus Dur di NU juga mengantarkan dia sebagai tokoh nasional dengan gagasan toleransi kebangsaaan yang menjalin hubungan antar umat beragama.
Gus Dur bahkan kemudian terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1999, sebelum dijatuhkan oleh MPR pada tahun 2001.
Tapi apakah sosok Gus Dur sebagai pemimpin nasional tidak membuat perannya menjadi amat sentral di NU?
Profesor Abdul A'la mengakui kharisma Gus Dur mempunyai kelebihan dan kelemahannya bagi NU.
"Di satu sisi, kehadiran Gus Dur di pentas nasional membuat orang tidak malu-malu mengaku sebagai orang NU. Menjadi semacam semangat bagi anak-anak muda NU untuk tidak malu lagi untuk mengaku sebagai NU."
"Kelemahannya, karena terlalu besar kadang-kadang apa yang disampaikan Gus dipatuhi secara tanpa tawar menawar lagi. Padahal Gus Dur maunya tidak seperti itu."
"Tapi karena terlalu kuat dan karena tidak ada yang menandingi, maka yang terjadi justru bertentangan dengan kehendak Gus Dur sendiri yang ingin NU menjadi masyarakat madani yang kritis tapi tetap apresiatif."
Ketika Abdurrahman Wahid meninggal dunia pada 30 Desember 2009, bukan hanya warga NU atau umat Islam saja yang ikut berduka tapi seluruh warga negara Indonesia dari berbagai suku, agama, maupun lapisan sosial ekonomi.
Delapan puluh tiga tahun sejak berdiri, seluruh rakyat Indonesia berduka atas tokoh NU yang membuktikan tegaknya prinsip kebangsaan dan kerakyatan sesuai khittah 1926.
Beban kebangsaan dan kerakyatan itu agaknya ikut membayang-bayangi Muktamar ke-30 di Makassar.